Songlit perdana hasil kolaborasi antara V-chan/Wintervina & Achan
Songlit ini didasari lagu 'Tegami' yang dinyanyikan Angela Aki.
--------------------------------------------
Mataku yang sedari tadi tenggelam dalam keruhnya Sungai Kapuas terpaksa
beralih pada kawanan remaja yang tengah melintas sambil bercekakak cekikik
tanpa henti. Bau kolonye mereka yang tajam dan berbaur di udara seketika
membuatku mual.
Kini pandanganku benar-benar tak mau lari dari ketiga remaja itu. Tawa
mereka belum juga susut, tapi kini kawanan itu mulai melambatkan langkah begitu
mendekati kolam setengah lingkaran yang bak barikade mengitari Replika Tugu
Khatulistiwa.
Si gadis yang di tengah―yang kulitnya seputih lilin dan mengenakan topi
fedora warna salem―mengeluarkan ponsel dari dalam tas. Sementara si teman yang
lengan jaketnya membelit pinggang menyodorkan tongsis. Tak lama kemudian, ketiganya mulai melakukan senam wajah:
mengerucutkan bibir, menjulurkan lidah,
mengedipkan mata.
Kini, aku tidak merasa yakin latar Replika Tugu Khatulistiwa itu
benar-benar penting untuk mereka abadikan daripada wajah mereka sendiri. Mereka
terus berfoto, sesekali mengecek hasilnya sambil terkekeh geli. Si rambut poni
mengambil alih tongsis dari tangan si
topi fedora. Dan pemotretan pun kembali berlanjut.
Berdasarkan taksiranku, gadis-gadis itu sebaya denganku.
Aku lima belas tahun, tapi sama sekali belum pernah melakukan hal-hal
menyenangkan seperti mereka. Tertawa puas sampai keluar air mata, berfoto di
tempat ramai tanpa kenal malu, dan berjalan berangkulan penuh persahabatan.
Hari-hariku kelewat monoton.
Seperti feri di timur Taman Alun-alun Kapuas ini, bolak-balik di
situ-situ saja. Mengantar penumpang dari Pontianak Kota ke Pontianak Utara
maupun sebaliknya.Tak ke mana-mana.
Masa mudaku yang seharusnya indah, hanya kulalui dengan belajar dan
belajar. Maka, tak heran bila nilai raporku selalu membuat orang berdecak
kagum―tapi tidak dengan kedua orangtuaku.
Aku siswi peraih nilai tertinggi Ujian Nasional SMP se-Kalimantan Barat
dua tahun lalu, tapi orangtuaku tak menganggapnya penting. Tahun pertamaku di
SMA, aku menyabet juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat nasional, tapi kata
Bapak itu sama sekali bukan apa-apa. Lalu, baru-baru ini, penghargaan kembali
aku raih. Juara I Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran fisika tingkat SMA
se-Kalimantan Barat. Namun, tetap, pujian tak pernah datang dari mulut Bapak
maupun Ibu.
Selalu Mahoni.
Pujian mereka hanya selalu untuk Mahoni, adikku.
Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, aku berusaha sekeras ini toh hanya
agar mereka dapat melihatku sekali saja. Memujiku sekali saja.
Gara-gara mengejar pengakuan mereka, perlahan aku jadi monster yang
menakutkan. Belajar seperti orang kesurupan. Kurang tidur. Kurang makan.
Bahkan, yang lebih menyedihkan, aku tak
punya satu pun teman.
Teman, ya? Ah, barangkali aku punya satu, tapi itu sekitar seminggu yang
lalu. Dia satu-satunya gadis di kelas yang tak pernah jemu mendekati dan
mengajakku bicara. Dengannya, aku saling berdiskusi tentang materi pelajaran,
fenomena alam, dan hal-hal menarik lainnya. Namun, semua itu mesti cepat
berakhir....
Aku ingat hari itu bagaimana aku memakinya, menumpahkan segenap rasa
frustasiku lantaran gagal mendapat nilai sempurna dalam UTS biologi. Itu karena
buku catatan biologiku yang dipinjamnya tak ia kembalikan. Dan di hari ujian,
anak itu malah menghilang. Alasannya baru kuketahui belakangan, itu pun dari
wali kelasku. Hari di mana temanku absen ke sekolah itu, ayahnya meninggal
dunia. Strok, begitu kabar yang kudengar.
Namun, semua terlambat. Sejak itu, aku dan dia tak pernah menegur satu
sama lain . Telanjur terjebak dalam peran ‘orang asing’ yang kami mainkan.
Aku kian takut pada diriku sendiri. Aku merasa... tersesat dan
kehilangan arah.
Tanpa sadar, aku sudah melangkah terlampau jauh meninggalkan diriku yang
sebenarnya demi mengejar pengakuan dari kedua orangtuaku. Sementara hati dan perasaanku semakin tumpul
saja.
Kini, semuanya sudah tak tampak penting lagi: retikulum endoplasma,
hukum Newton, konfigurasi elektron, dan kawan-kawannya. Aku sudah lelah... dan
begitu muak dengan diriku sendiri.
Belum lagi kata-kata Agatha Christie di salah satu bukunya seakan
mengejekku. ‘Hampir semua orang sukses tidak berbahagia. Itu sebabnya mereka
sukses―mereka harus meyakinkan diri sendiri dengan cara mencapai sesuatu yang
mencolok di mata umum,’ begitulah yang dia bilang.
Ya, kesalahanku. Seharusnya aku tak menemukan dan membaca buku sialan
itu sewaktu berkunjung ke Perpustakaan Daerah tiga hari lalu. Sebelumnya, aku
juga tak pernah repot-repot menghampiri rak buku fiksi bila berada di sana.
Namun, segala sesuatu butuh perkecualian, sebagaimana yang terjadi padaku hari
itu. Duduk manis dan tenggelam dalam khayalan Agatha.
Tawa bocah perempuan yang dikuncir ekor kuda membuyarkan lamunanku.
Bunyi sepatunya yang berdecit tiap melangkah mengundang perhatian orang. Dengan
mata berbinar, ia mendekati badut Masha yang tengah berdiri tak jauh dari
jejeran bunga.
“MALSYA!” seru anak itu pelat. Jemarinya yang mungil menunjuk pada badut
bertudung dadu dengan poni membingkai wajah. Lalu, si badut pun melambaikan
tangan.
Di belakangnya, sang ayah tampak menyusul sambil membawa seutas balon.
Kemudian, mereka berfoto bersama si badut. Satu,
dua, tiga.... Seketika, tawa bahagia pun dibekukan oleh kamera.
Begitulah. Momen-momen seperti itu entah kenapa selalu berhasil membuat
mataku berawan.
Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku tersenyum bersama Bapak dan Ibu.
Kalaupun pernah, itu sudah lama sekali. Begitu lama, sampai aku tidak mampu
mengingatnya.
Seorang lelaki berambut gimbal yang menenteng kamera DSLR bersandar di
pagar pembatas taman. Tak lama kemudian, ia menyulut sebatang rokok. Menyesap
asapnya dalam-dalam. Matanya yang semula keras menjadi layu. Memandang sendu
pada Sungai Kapuas yang membentang di hadapan.
Apakah tiap orang diam-diam punya kesedihan yang sama?
Aku ingat akan biji-biji saga yang merah menyala di kawasan Arboretum
Sylva Untan. Biji-biji itu, kendati kecil, punya kemampuan bertahan yang
mencengangkan. Tak hancur meski terinjak kaki-kaki manusia, terlindas ban
kendaraan, atau tertimpa hujan dan tersengat matahari.
Andaikan bisa, aku ingin sekali sekuat biji saga yang mungil itu. Terus
bertahan di tengah badai hidup yang kian menerjang. Namun, entah kenapa, aku
tidak merasa yakin dapat melalui semua kesulitan ini.
Langit yang tadinya laksana disepuh emas kini menjelma semerah inai.
Matahari yang semula berjaya perlahan-lahan tergelincir.
Aku mencuil sedikit gulali yang sedari tadi kuanggurkan.
Manis.
Ya, begitulah. Kalau hidup sudah tak lagi menawarkan hal-hal manis,
mungkin kau hanya butuh sedikit pelarian. Pada makanan, misalnya, seperti yang
tengah kulakukan.
Keadaan kian hibuk di Taman Alun-alun Kapuas pada jam-jam begini.
Orang-orang menyemut hendak menaiki kapal wisata. Tangisan anak kecil yang
minta dibelikan jajanan. Kumpulan anak muda yang asyik bercengkerama di kursi
payung. Perempuan tua dengan mulut berminyak yang menyantap sosis dan hekeng
dalam diam di sampingku. Juga lelaki buntak yang melangkah gegas―bahkan nyaris
berlari dengan mata terpaku pada layar ponsel pintar miliknya. Memburu Pokemon,
kurasa.
Semua keramaian dan keriuhan ini entah kenapa membuatku begitu nyaman
menikmati kesendirian. Seperti kau sedang menari berputar-putar di atas
panggung dengan jutaan penonton di sekelilingmu yang membeku.
Lalu aku kembali melepas pandangan ke arah sungai. Tuter feri berbunyi
panjang-panjang, terasa menenangkan. Seperti seorang ibu yang memanggil-manggil
anaknya untuk pulang.
Pulang.
Aku terkesiap mendengar kata itu.
Sekonyong-konyong, aku ingat Ibu. Ibu yang menyukai pepohonan, hingga
menamai aku dan adik dengan Cemara dan Mahoni.
Bukan, Ibu bukanlah ahli botani. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga
biasa yang sehari-hari menyulap makanan lezat di meja dapur. Dia memuja Mahoni,
begitu pun sebaliknya. Hanya itu yang bisa aku pikirkan tentang Ibu. Terlalu
menyedihkan bukan?
Usiaku dan Mahoni hanya terpaut dua tahun. Dia tipe gadis periang dan
aku suram. Dia senantiasa tersenyum sedangkan aku murung. Dia cantik dan aku
tidak.
Begitu banyak alasan untuk mencintai gadis seperti Mahoni, bukan?
Aku tidak pernah lupa bagaimana suatu hari Ibu masuk ke kamarku dengan
tampang masam. Jemarinya yang gemuk membekap hidung. “Ara, tolong jangan
melukis lagi, dong. Ibu sudah tidak tahan dengan segala bau cat ini.” Lalu
pandangannya jatuh ke lantai sebelum menghardik lagi, “Aduh, Ara! Lihat, lantai
jadi berlepotan cat di sana-sini. Pokoknya, tidak ada lukis melukis lagi!”
Aku sejurus membisu, menatap alis Ibu yang meninggi dan wajah gusarnya.
Tanganku yang memegang kuas mendadak lemas. Masalahnya, Ibu tidak pernah
mengerti bagaimana mengagumkannya virtuoso dengan nada-nada indah yang mereka
mainkan, atau betapa hebatnya ilustrator dengan gambar-gambar penuh keajaiban
yang mereka lahirkan.
Ibu tidak pernah mau mengerti.
Seakan semua belum cukup untuk menyakitiku, Ibu berkata lirih di muka
pintu sebelum keluar, “Coba deh seperti Moni. Bikin kue, bersih-bersih di
dapur... Ini kok hobinya malah mengotori rumah saja.”
Sejak itu, aku sama sekali tidak pernah melukis lagi.
Dulu, aku melukis sebagai bentuk pelarian dari kesedihan. Sebagaimana
yang Pablo Picasso bilang, ‘Seni lahir dari kesedihan dan penderitaan.’ Dan
kini, dengan segala kesedihan yang melingkupiku, bukan seni yang tercipta,
melainkan hanya depresi.
Aku di masa lalu selalu berbau cat minyak dan tiner. Tenggelam
berjam-jam di depan kanvas demi menyulap kain putih itu menjadi lukisan abstrak.
Sementara aroma manis dengan setia menempel pada Mahoni, yang hari-harinya
banyak dihabiskan di dapur membuat kue. Serbuk tepung menempel di pipi, sedang
jemarinya dengan tekun menguleni jeladren. Lalu Ibu akan datang untuk membantu.
Mereka saling bercerita sambil menyemburkan tawa. Selanjutnya, Bapak akan
datang, mencicipi kue buatan mereka dan bilang, “Ini kue terenak yang pernah
Bapak makan.”
Mereka benar-benar gambaran keluarga bahagia. Tentunya, bila aku tidak
pernah ada.
Suara muazin lapat-lapat terdengar di tengah keriuhan pengunjung taman.
Seketika aku menghentikan pikiran yang sejak tadi melayap. Malam sudah turun.
Saatnya untuk pulang.
Pulang.
Lagi-lagi kata itu. Kapan ya kehadiranku benar-benar di rindukan oleh
seisi rumah?
Aku mengeluarkan secarik kertas dari dalam tas, lalu mulai menulis.
Dear, kamu yang membaca surat ini.
Di mana dan apa yang sedang kamu lakukan sekarang?
Aku yang berusia 15 tahun ini, menyimpan benih kegelisahan yang tak pernah kuungkapkan pada siapa pun. Jika surat ini kutulis dan kutujukan untuk diriku di masa depan, kuyakin aku bisa mengungkapkan segalanya dengan jujur. Sekarang, aku hampir menangis, putus asa dan hampir kehilangan jati diri. Kata-kata siapa yang harus kupercaya agar aku bisa melangkah kembali? Hatiku ini hanya ada satu dan telah berkali-kali hancur, pecah dan tercerai-berai. Meski dirundung duka, aku terus hidup menjalani masa kini.
Kertas tersebut kulipat menjadi sebuah perahu dan kuletakkan di atas air
Sungai Kapuas. Entah kepada siapa surat berbentuk perahu kertas itu akan
berlabuh, aku tidak peduli. Setidaknya, aku telah mengatakan apa yang sedang
aku rasakan. Perahu kertas itu semakin menjauh. Memang terkesan konyol menulis
surat, kemudian melipatnya menjadi sebuah perahu kertas dan menghanyutkannya di
Sungai Kapuas, tapi aku tidak tahu harus bercerita kepada siapa lagi. Aku pun
berpaling meninggalkan Taman Alun-alun Kapuas.
***
Bel berbunyi menandakan jam pelajaran terakhir telah usai. Begitu guru
keluar dari kelas, para siswa mulai saling menghampiri. Suara alat tulis yang
ditaruh ke dalam tempat pensil dan suara krasak-krusuk buku-buku yang
dimasukkan ke dalam tas bercampur dengan obrolan di kelas. Aku pun mengemasi
buku dan alat tulisku.
Namun, tanganku terhenti ketika seseorang tiba-tiba berdiri di sebelah
mejaku. Aku mendongak untuk melihat wajah orang tersebut. Ah, ternyata Rina.
Masih ingat dengan satu-satunya gadis di kelas yang tak pernah jemu mendekati dan mengajakku bicara? Yang dengannya aku saling berdiskusi tentang materi pelajaran, fenomena alam, dan hal-hal menarik lainnya. Namun aku malah memarahinya dan menumpahkan rasa frustasiku padanya hanya karena ia terlambat mengembalikan buku catatan biologi milikku. Ya. Gadis itu adalah Rina, teman sekelas dan teman satu kelompokku untuk tugas mata pelajaran kesenian.
Masih ingat dengan satu-satunya gadis di kelas yang tak pernah jemu mendekati dan mengajakku bicara? Yang dengannya aku saling berdiskusi tentang materi pelajaran, fenomena alam, dan hal-hal menarik lainnya. Namun aku malah memarahinya dan menumpahkan rasa frustasiku padanya hanya karena ia terlambat mengembalikan buku catatan biologi milikku. Ya. Gadis itu adalah Rina, teman sekelas dan teman satu kelompokku untuk tugas mata pelajaran kesenian.
Rina sepertinya ragu untuk mulai berbicara denganku.
"Ada apa?" tanyaku memulai pembicaraan karena tak ingin
membiarkannya berdiri mematung lebih lama di sebelah mejaku.
"Mmm... aku cuma mau mengingatkan kalau hari ini kelompok kita akan
mengerjakan tugas membuat lagu. Tempatnya di rumahku, jam 3 sore," ujar
Rina singkat, tapi cukup jelas.
"Oke. Makasih udah mengingatkan."
Rina mengangguk, kemudian berbalik dan berjalan kembali ke tempat
duduknya.
Begitu selesai mengemasi buku dan alat tulis, aku langsung berjalan
meninggalkan kelas, sementara Rina tampak masih sibuk di mejanya.
Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar. Berganti baju,
kemudian makan siang di dapur tanpa berbicara sepatah kata pun meski ada
Moni dan Ibu yang sedang menonton di ruang keluarga. Mereka juga tidak
berbicara padaku. Sekadar berbasa-basi pun tidak. Sedangkan Bapak masih belum pulang
dari kantor.
Sepertinya, acara TV yang mereka tonton benar-benar menarik, karena Ibu
dan Moni terlihat 'lebih seru' berkomentar satu sama lain. Coba kalau cuma aku
yang menonton TV bersama Ibu, keseruan seperti itu tidak pernah terjadi. Ibu
hanya akan diam selama menonton.
Alih-alih seperti pohon cemara yang tumbuh menjulang tinggi hingga mudah dikenali dari jauh, aku ini lebih seperti sisik ikan yang diletakkan di depan mata mereka. Walaupun ada di hadapan mereka, tetap saja 'tak terlihat'.
Alih-alih seperti pohon cemara yang tumbuh menjulang tinggi hingga mudah dikenali dari jauh, aku ini lebih seperti sisik ikan yang diletakkan di depan mata mereka. Walaupun ada di hadapan mereka, tetap saja 'tak terlihat'.
Selesai makan, aku langsung kembali ke kamar. Masih ada waktu sebelum ke
rumah Rina, tapi aku mulai bersiap-siap ke rumahnya saja. Aku tidak perlu
berlama-lama di rumah, di mana keberadaanku hanya seperti sisik ikan yang
transparan.
Tak memerlukan waktu lama, aku pun selesai bersiap-siap dan keluar dari
kamar.
"Bu, aku mau ngerjain tugas kelompok di rumah Rina," ujarku
berpamitan pada Ibu.
"Iya." Cuma itu yang keluar dari mulut Ibu sementara pandangan
beliau tidak beralih dari TV.
Aku menghela napas. Selalu seperti itu.
Rumah Rina cukup jauh dari rumahku. Jadi aku pergi dengan sepeda motor.
Seperti biasa, siang ini matahari bersinar cerah di langit yang tak
berawan.Tinggal di kota khatulistiwa ini sejak lahir, aku pun terbiasa dengan
panasnya sinar matahari yang menyinari Pontianak. Namun, angin yang berembus selalu terasa lebih sejuk.
"Ara...! Masuk, masuk... Udah lama Ara nggak main ke rumah,"
sambut Kak Zia, kakak Rina, dengan ramah. Kak Zia memang mengenalku karena
kedekatanku dengan Rina dulu.
"Duduk aja... Rina baru aja nyampe. Lagi makan siang di dapur. Ara
udah makan?" tanya Kak Zia setelah mempersilakan aku duduk di ruang tamu.
"Udah, Kak," jawabku sembari mendudukkan diri di atas sofa.
"Tunggu sebentar, ya...."
Aku mengangguk kecil. Kak Zia berlalu masuk meninggalkanku sendirian di
ruang tamu. Kudengar suara orang-orang berbicara dari dalam. Sepertinya ada
tamu lain di rumah ini selain aku, karena yang aku tahu Rina tinggal bertiga
dengan kakak dan ibunya setelah ayahnya meninggal.
Aku melihat ke sekeliling ruangan. Tak banyak yang berubah sejak
kunjunganku terakhir ke sini. Foto-foto yang dipajang masih pada tempatnya.
Kebahagiaan dan keharmonisan keluarga ini tampak dari foto-foto tersebut. Senyum
mereka bukan senyum buatan, tapi senyum yang memancarkan kebahagiaan. Berbeda
dengan foto keluarga di rumahku yang formal dan datar.
"Ara..."
Aku tersadar dari lamunanku tentang foto begitu mendengar suara Kak Zia.
Kak Zia muncul kembali sembari membawa nampan berisi minuman dan sepiring kue.
"Rina udah selesai makan, kok. Bentar lagi ke sini," ujar Kak
Zia seraya meletakkan gelas minuman dan piring kue di atas meja.
"Temannya Rina, ya?"
Aku terkejut mendengar suara yang asing di telingaku. Ketika menoleh ke
arah datangnya suara yang berasal dari belakang Kak Zia,tampak seorang pria sedang
menggendong bayi laki-laki yang usianya mungkin belum sampai satu tahun.
Senyumnya sama ramahnya dengan Kak Zia.
"Iya," jawabku.
"Ini paman kakak. Adik Ibu yang bungsu. Silakan diminum, kuenya
juga dimakan, ya," ujar Kak Zia yang duduk di depanku. Paman Kak Zia masih
tetap berdiri di belakang sofa.
"Ara..." sapa Rina yang muncul dari dalam sembari membawa
gitar.
Aku menolehnya.
Tiba-tiba, bayi laki-laki yang digendong oleh Paman Rina menangis.
"Kenapa menangis?" Kak Zia tampak khawatir. Rina juga berhenti
di dekat bayi tersebut.
"Iya, Sayang...." Ibu si bayi pun datang dengan tergesa-gesa.
Dan pemandangan di hadapanku pun berubah menjadi pemandangan penuh
keharmonisan. Semua perhatian tercurah pada bayi laki-laki itu. Membuatku iri.
Apa waktu aku kecil dulu, perhatian Ibu dan Bapak juga tercurah sebanyak itu?
Kalau "ya", sejak kapan semuanya berubah? Aku tahu jawabannya. Semua
berubah sejak Moni lahir.
Aku hanya bisa berdoa semoga perhatian itu tidak berkurang jika bayi
laki-laki tersebut punya adik.
Si Ibu mengambil bayi laki-laki tersebut dari gendongan si ayah,
kemudian duduk di sofa.
"Popoknya basah?" tanya Rina.
"Iya... Kita ganti popok dulu, ya...." Si ibu berdiri kembali
setelah memeriksa popok si bayi, lalu berjalan masuk ke dalam diikuti si ayah.
Tinggal aku, Rina, dan Kak Zia di ruang tamu.
"Kayaknya aku datang terlalu cepat," ujarku.
"Nggak apa-apa kok. Kita mulai aja dulu sambil menunggu yang
lain."
Aku cuma mengangguk. Tugas kelompok untuk mata pelajaran kesenian kali
ini adalah membuat lagu. Padahal aku lebih suka melukis. Namun, sayangnya,
tugas melukis sudah diberikan kepada kami sebagai tugas individu sebelum UTS.
Rina meletakkan alat tulis dan bukunya di atas meja dan menaruh gitar di
permukaan sofa.
"Mau bikin lagu?" tebak Kak Zia melihat gitar yang dibawa oleh
Rina.
"Iya. Tugasnya disuruh bikin lagu," jawab Rina.
"Aah... jadi ingat waktu SMA dulu."
Kak Zia mengambil gitar dan mulai memainkannya.
"Haikei, kono tegami yondeiru anata wa...Doko de nani wo shiteiru
no darou...Juugo no boku ni wa,dare ni mo hanasenai nayami no tane ga aru no
desu... Mirai no jibun ni atete kaku tegami nara... Kitto sunao ni uchiake
rareru darou..."
Lagu itu terdengar asing bagiku. Ditambah lagi liriknya bukan bahasa Indonesia
atau bahasa Inggris. Namun, entah kenapa, aku menyukainya. Suara Kak Zia memang
merdu. Yang kutahu, Kak Zia memang multitalenta.
"Ooo... Zia kalo nyanyi pasti langsung mendung. Itu temannya Rina
bawa jas hujan nggak? Ntar pulangnya kehujanan loh," ujar Paman Rina
mengomentari suara Kak Zia. Sontak, Kak Zia langsung berhenti.
"Yeee... biarin kalo hujan. Biar Pontianak adem," balas Kak
Zia."Oya, jadi ingat. Paman tau nggak, pernah nih aku nganterin Rina ke
sekolah. Pas berangkat tuh langit udah mendung. Eh beneran pas di jalan hujan
turun. Hujannya deras banget. Aku sampai basah kuyup. Tapi Rina yang dibonceng nggak
basah. Kena hujan setetes aja nggak. Sampai di sekolah, ibu nelpon. Ibu cuma
nanya, 'Rina kehujanan?'. Terus ngomel karena khawatir Rina nanti bisa sakit
kalau kehujanan. Padahal aku yang basah kuyup sampai menggigil, ibu nggak nanya
sama sekali. Hahahaha..."
"Hahahaha..." Paman Rina ikut tertawa mendengar cerita Kak
Zia, sedangkan Rina cuma tersenyum.
Aku mengernyitkan dahi. Bingung karena tidak menemukan hal yang lucu
dari cerita Kak Zia. Kenapa Kak Zia menceritakannya sambil tertawa?
"Terus pernah juga, waktu aku jemput Rina pulang dari sekolah, waktu
itu panas banget. Aku sakit kepala, tapi tetap jemput Rina. Pas di jalan
pulang, tiba-tiba sakit kepalanya makin parah sampai hampir jatuh dari motor.
Sampai di rumah, waktu cerita ke ibu, ibu panik, langsung nanyain Rina luka
nggak. Abis itu aku cerita kalau aku sakit kepala, ibu komentarnya cuma
'oh...'. Haduuh...Sedih... kayak anak Ibu cuma Rina. Ibu memang luar biasa...luar
biasa sayangnya sama Rina. Hahaha..." lanjut Kak Zia penuh ekspresi dan diselingi
tawa.
"Hahahaha..."
Lagi-lagi Paman Rina ikut tertawa.
Kenapa? Kenapa Kak Zia bisa menceritakan hal seperti itu sambil tertawa?
Bukannya itu adalah hal yang menyakitkan? Aku tidak mengerti dengan Kak Zia.
"Soalnya aku kan anak ayah. Jadi ingat ayah lagi, kan. Dulu ayah
pernah bilang kalau ibu bukannya nggak sayang sama aku, tapi bagi ibu, aku udah
lebih dewasa dan lebih mandiri dari Rina," lanjut Kak Zia sembari
mengacak-acak rambut Rina. Bukannya sok tahu, tapi di mataku, Kak Zia tampak
sangat tulus dan sangat menyayangi Rina.
Paman Rina masih terkekeh.
Aku melirik Rina. Kulihat di wajahnya terukir senyum sedih. Entah apa
yang sedang Rina pikirkan. Tak lama kemudian satu per satu anggota kelompokku
datang. Namun aku jadi tidak bisa berkonsentrasi mengerjakan tugas kelompok.
Pikiranku dipenuhi oleh wajah polos Kak Zia dan tawanya ketika menceritakan
pengalamannya tadi. Lagipula, menulis lagu memang bukan keahlianku. Dan
untungnya teman-temanku satu kelompok bisa diandalkan. Jadi tugas kami dapat
diselesaikan pukul 5 sore meskipun lagu yang kami buat sangat sederhana.
Di sepanjang jalan pulang, aku terus memikirkan cerita Kak Zia. Bertemu
dengan Kak Zia dan melihatnya bercerita tadi membuatku merasa ada sesuatu yang
aneh menyusup ke dalam hatiku.
Tiba-tiba, aku ingin menjadi seperti Kak Zia yang selalu tersenyum dan
menyayangi dengan tulus. Sesuatu yang tidak pernah bisa kulakukan sampai detik
ini. Selama ini, aku hanya mempertanyakan kasih sayang dan perhatian dari Bapak
dan Ibu. Padahal, tanpa sadar, aku sendiri belum menyayangi mereka dan
memberikan perhatian pada mereka dengan tulus. Aku hanya 'mengejar' pujian dan
perhatian dari mereka.
Betapa tidak dewasanya diriku.
Andai aku seumuran dengan Kak Zia, apa yang akan kukatakan pada diriku
yang sekarang?
Gerbang kompleks perumahan tempatku tinggal semakin dekat. Aku pun
kembali memfokuskan perhatianku pada jalan. Sesampainya di depan rumah, kulihat
sepeda motor Ayah diparkir di garasi. Ayah sudah pulang. Aku pun memasukkan
sepeda motor ke dalam garasi. Setelah mengucapkan salam, aku membuka pintu
rumah.
"Ibu... Bapak... Moni... Ara pulang," ujarku seraya tersenyum
untuk pertama kalinya.
Ibu dan Bapak terkejut melihatku tersenyum. Begitu juga dengan Moni.
Namun, aku tetap tersenyum. Aku telah membulatkan tekad. Bahwa, mulai
hari ini, aku yang akan menunjukkan perhatian dan kasih sayang pada mereka.
Tidak peduli apakah sikap mereka masih akan tetap sama seperti sebelumnya.
"Bapak udah lama pulang dari kantor?"
"Udah. Kayak biasa."
"Ibu masak apa hari ini?"
"Ibu masak sup ayam."
"Moni lagi baca apa?"
"Komik Detective Conan."
Aku masih tersenyum. Aku harap ini adalah awal yang baik. Namun, entah
kenapa terasa sangat ganjil. Seolah aku ini sedang ‘meninggalkan tabiat’-ku.
Aku langsung masuk ke dalam kamar. Kulihat jendela kamarku masih
terbuka. Aku lupa menutupnya sebelum pergi ke rumah Rina. Untungnya, jendela
kamarku dilengkapi dengan terali besi yang cukup rapat, sehingga masih
terbilang aman dari pencuri.
Ketika tengah menggantung tas, aku melihat sebuah pesawat kertas di atas
meja belajarku. Seingatku, aku tidak membuat pesawat kertas sebelumnya. Hanya
sebuah perahu kertas yang kuhanyutkan di Sungai Kapuas. Di rumah juga tidak ada
yang suka masuk ke kamarku yang dipenuhi bau cat ini. Jadi, pesawat kertas ini
bukan buatan orang di rumah. Satu-satunya cara pesawat kertas ini masuk adalah
dari jendela kamarku yang tidak ditutup.
Kuambil pesawat kertas tersebut
dan kuperhatikan dengan saksama. Sepertinya ada tulisan di dalam lipatan kertas
tersebut. Kubuka lipatan kertas tersebut untuk membaca isinya.
Dear,
Terima kasih atas suratnya.
Ada hal yang harus kusampaikan kepada kamu yang berusia 15 tahun. Dengan apa dan ke mana gerangan arah yang harus kau tuju?
Terus tanyakanlah lebih dalam kepada dirimu dan kamu akan menemukan jawabannya. Mengarungi badai di lautan masa muda itu adalah sebuah perjuangan keras. Namun, teruslah berlayar menuju pantai masa depan dengan perahu mimpi.
“Aku hampir menangis, putus asa dan hampir kehilangan jati diri. Kata-kata siapa yang harus kupercaya agar aku bisa melangkah kembali?”
Sekarang, janganlah menangis, janganlah putus asa. Di saat kamu hampir kehilangan jati diri, teruslah melangkah dan tetap percaya pada suara hati nurani. Aku yang sudah dewasa ini pun, sering terluka dan menempuh malam terjaga. Tetapi, dalam manis pahitnya kehidupan, aku terus hidup menjalani masa kini. Segalanya dalam kehidupan ini memiliki suatu makna. Janganlah takut, wujudkanlah impianmu. Keep on believing.
Di masa apa pun, kamu takkan pernah bisa menghindari kesedihan. Tetapi perlihatkanlah senyumanmu.
Ayo kita jalani masa kini.
Dear, kamu yang sedang membaca surat ini. Aku selalu berdoa akan kebahagiaanmu.
Tidak salah lagi. surat ini adalah balasan dari surat yang kulipat menjadi
perahu kertas dan kuhanyutkan di Sungai Kapuas kemarin. Namun, siapa yang
menulis surat ini? Darimana dia tahu alamat rumahku? Aku tidak bisa menebaknya.
Tidak ada petunjuk sama sekali tentang siapa pengirim surat ini. Tidak ada nama
pengirim yang tercantum di surat ini. Aku berjalan mendekati jendela sambil
tetap memegangi surat tersebut.
Apa surat ini dari diriku sendiri di masa depan? Sesuatu seperti time
leapt? Namun, bukankah time leapt masih berupa teori hingga saat
ini? Aku menghela napas, menyerah untuk memikirkannya lebih lanjut. Yang pasti,
ada seseorang di luar sana yang menjadi tempat mengungkapkan kegelisahanku.
Tiba-tiba angin berembus masuk dari jendela, dan surat tersebut tetap
kupegang erat-erat.
Aku tak perlu berubah menjadi orang lain agar mendapat perhatian Bapak
dan Ibu. Namun, aku akan selalu tersenyum dan menyayangi mereka dengan tulus.
Aku percaya pada surat ini bahwa di masa apa pun, kita takkan pernah bisa
menghindari kesedihan, tetapi perlihatkanlah senyuman kita.
Aku menutup jendela kamar, memasukkan surat tersebut ke dalam laci meja
belajarku, kemudian keluar kamar dan menghampiri Ibu di dapur.
“Ibu...” sapaku padanya yang tampak sibuk mencuci sayuran.
“Ya...”
“Ada yang bisa aku bantu?”
Seketika Ibu berhenti dan menatapku dengan pandangan ada-apa-dengan-Ara.
Bapak dan Moni ikut melirik ke arahku, tapi aku tetap berusaha tersenyum.
“Ada yang bisa aku bantu?” ulangku.
“I...Iya... Ada. Bantu Ibu memotong sayurnya, ya,” ujar Ibu setengah
tidak percaya.
“Oke,” ujarku sembari mengambil pisau dan talenan.
Tekadku sudah bulat, mulai hari ini, aku-lah yang akan memberi perhatian
dan kasih sayang pada Bapak, Ibu, dan Moni.
SELESAI
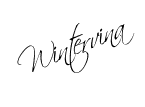








0 komentar:
Posting Komentar